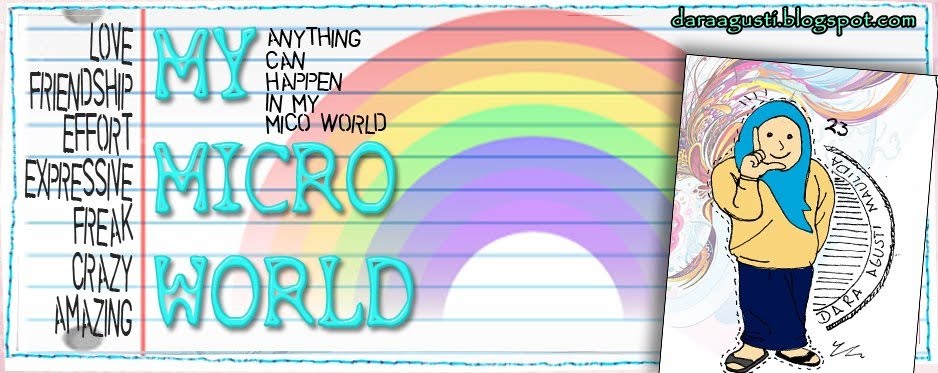"Bagi mereka, esensi rumah lebih daripada itu..."
Semilir angin gersang berhembus. Hawa panas yang tak biasa terasa menjerat tubuh. Aku bersembunyi di balik tembok rasis yang menghilangkan jutaan nyawa tak berdosa serta merampas masa depan jutaan nyawa lainnya. Pupilku melebar, berkeliaran mencari pantulan cahaya yang kukenal. Nihil, semuanya asing bagiku. Aku hanya bisa berusaha sekuat hati untuk memaksa perasaanku agar lebih tenang.
Hari ini aku mendapat amanah baru, menjadi relawan medis utusan Republik Indonesia yang harus bertugas di daerah konflik Palestina-Israel, Gaza. Dentuman bom sesekali terdengar, bersahut-sahutan dengan takbir yang lantang dari bibir para pemuda dan anak-anak yang tak pernah menyerah. Semua membaur, menciptakan sebuah harmoni tanpa arti.
Barak pengungsian terletak hampir di sudut paling ujung jangkauan mataku. Dengan tangan melindungi kepala dan badan yang dibungkukkan, aku memutuskan untuk berlari menuju barak itu –sebuah tenda darurat tempat korban perang serta wanita dan anak-anak dikumpulkan- sampai pada akhirnya seorang ibu berjilbab merah marun menyambut kedatanganku. Pandangannya teduh, membawa isyarat seolah perang telah lama selesai. Mungkin ia adalah seorang istri yang ditinggal perang oleh suaminya, atau ibu yang telah kehilangan buah hatinya akibat konflik ini.
“Salam ‘alaikum,” ucapnya.
“’Alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,” jawabku. “Perkenalkan, nama saya Zahra, relawan medis dari Indonesia. Insya Allah saya akan berada di sini selama beberapa bulan kedepan.”
“Semoga Allah memberkatimu, nak. Saya Umi Faras. Mulai sekarang tinggallah di barak ini. Kami sangat senang atas kehadiranmu.”
“Terima kasih, Umi.”
Awan senja kemerahan menari pulang, digantikan oleh datangnya langit hitam bertabur bintang. Aku menerawang jauh, berpikir seandainya aku dapat melihat menembus gelap malam dan mengetahui rencana Tuhan. Tanah ini terlalu suci untuk dijadikan ladang pertumpahan darah. Anak-anak itu terlalu berharga untuk mati terbunuh. Tuhan, apa yang sedang Kau rencanakan?
***
Deru helikopter Apache menabuh gendang telinga. Bunyi rentetan senjata menunggu mangsa. Dengan perlahan aku membalut kaki seorang anak lelaki yang terkena ledakan bom. Namanya Zayed, bocah berusia 11 tahun yang begitu berani menentang Israel. Ia bersama teman-temannya adalah pejuang sejati, anak-anak yang tak takut mati. Mereka adalah pejuang yang melawan senjata canggih para tentara Zionis dengan tangan yang siap melemparkan batu.
“Mengapa kalian begitu berani melawan tentara Zionis?” tanyaku seusai menangani kaki Zayed.
“Karena kami punya hak untuk hidup, belajar dan bermain. Tapi orang-orang Israel merampas itu semua dari kami,” jawab salah satu dari mereka. Ucapan itu bernada sederhana dan terus terang.
“Aku tahu itu kawan, dan itu bukanlah alasan yang salah.”
Masih ada dua anak lain yang terluka, Hamza dan Aseel. Sedari tadi mereka merintih menahan pedih dan hanya meratapi darah yang tak kunjung kering. Aku memeriksa keadaan Aseel, lantas menemukan sesuatu yang ganjil. Sebuah luka menganga yang terlalu dalam bagi pergelangan tangan mungilnya bersarang tanpa kasih. Aseel harus segera diamputasi. Aku bersama rekanku memutuskan mengamputasi tangan kanan Aseel dengan peralatan seadanya. Proses amputasi selesai beberapa jam kemudian sementara hari mulai menenggelamkan mentari. Kami mengantar Aseel menuju barak pengungsian.
Pengaruh obat bius yang hanya bertahan sebentar mulai hilang. Gadis kecil itu membuka mata, sarafnya mulai tajam kembali.
“Aseel, kau baik-baik saja?” Aku mencoba membuka percakapan.
“Apa yang terjadi?” Ia bertanya dengan segenap kepolosan kanak-kanak.
“Kami memutuskan mengamputasi tangan kananmu. Ledakan bom itu berdampak bahaya jika dibiarkan.”
Iris matanya yang berwarna coklat lumpur berkilauan, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia melihat tangan kanannya yang tak utuh lagi. Dalam sakit ia tersenyum. Senyum yang indah, sungguh seperti bunga. Anak perempuan yang masih 8 tahun itu tak gentar, tak takut pada apa yang dihadapinya.
“Biarlah, yang hilang hanya sebelah kanan. Aku masih punya tangan kiri. Lihat! Bahkan ia masih berfungsi seperti dulu,” Aseel menggerakkan tangan kirinya. “Walau tak ditemani tangan kanan...”
“Kau memang gadis pemberani, Aseel.” aku memujinya. “Hari sudah malam, maukah kau jika aku membacakan dongeng pengantar tidur untukmu?”
“Aku sangat berterima kasih jika kau bersedia, Zahra.”
Aku menceritakan padanya tentang kisah Gadis Berbaju Merah dan Serigala. Ia menyimaknya dengan khidmat. Ketika aku mengatakan bahwa gadis berbaju merah itu tidak pernah kembali ke rumahnya karena dimakan serigala, tiba-tiba ia memotong ceritaku.
“Tidak, Zahra. Gadis berbaju merah itu tidak dimakan serigala. Tapi ia dibunuh oleh orang-orang Israel.”
Aku tersentak, bagaimana bisa anak sekecil Aseel berpikiran seperti itu. Konflik panjang yang dialaminya telah meninggalkan trauma psikologis yang begitu hebat. Aku memandangnya lekat-lekat, ia masih terlalu muda untuk mengalami hal seberat ini.
“Zahra, aku rindu ayahku. Sejak konflik ini ia pergi dan tak pernah kembali. Aku juga rindu rumahku yang hancur berkeping karena serdadu penjajah Zionis. Maukah kau menceritakan padaku tentang rumahmu disana?” Ia meminta dengan tulus.
Aku memandangnya, menghela nafas dan mulai menjawab.
“Bagiku, rumah adalah tempat yang menyambutmu dengan senyum, tempat yang membuatmu tentram di dalamnya. Dan –apa yang orang katakan rumah- milikku itu bukanlah sebuah rumah bagiku.”
“Mengapa? Bukankah di negerimu banyak bangunan mewah yang bisa membuatmu tidur nyenyak?”
“Kau tahu? Mungkin tempat yang kutinggali adalah salah satu dari bangunan mewah yang kau maksud. Tapi ia hanya indah dalam khayal, Aseel.”
“Maksudmu?” ia tampak tak mengerti.
“Aku tak suka individualisme yang ada disana. Orang-orang di rumahku terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing...”
Hening.
Aku mengajak Aseel keluar dari barak. Kami duduk di bawah pohon zaitun, diantara semak khurfeish.
“Sekarang giliranmu, Aseel. Ayo ceritakan padaku tentang rumahmu.”
“Aku sedang merebut rumahku...” ia diam sesaat, melemparkan kerikil kecil disampingnya. “Dahulu aku tinggal bersama ayah di sebuah rumah sederhana, tapi penuh cinta kasih. Ayah bilang ibuku meninggal saat melahirkanku. Sejak kecil aku diasuh oleh adik ayah, Umi Faras.”
“Jadi, Umi Faras itu bibimu?”
“Ya, begitulah.” Aseel mengatur nafas, melemparkan kerikil untuk kedua kalinya. “Rumah kami terletak di desa Al ‘Izariyah, sebuah desa yang indah nan damai. Tapi semua itu berubah ketika serdadu Zionis datang.”
“Apakah rumahmu dekat dari sini?”
“Lumayan... jika kau mau, aku akan menunjukkan padamu besok.”
“Baiklah, Aseel. Lebih baik kau tidur sekarang, hari sudah larut. Ayo kita kembali ke barak.”
***
Seperti janjinya, hari ini Aseel mengantarku ke desa Al ‘Izariyah, salah satu desa yang dibelah oleh tembok pemisah hasil kerja penjajah Zionis untuk mengurung warga Palestina. Aseel menghembuskan nafas kuat-kuat, lalu berkata “Bisakah kau membayangkan apa yang ada di balik tembok itu, Zahra?”
“Aku tak pernah melihatnya, dan aku rasa untuk membanyangkannya pun aku tak sanggup.”
“Rumahku terletak di balik tembok itu...” ia menunjuk pada satu titik. “Aku rindu ayah...”
“Sabarlah Aseel, suatu saat nanti kau pasti akan bertemu dengan ayahmu.”
Aseel tampak berpikir keras. Raut wajah yang biasanya seperti bunga kini tampak berbeda. Matanya tetap tertuju pada titik yang ia tunjukkan padaku beberapa saat lalu.
“Apa yang kau pikirkan?” tanyaku.
“Rumah...” jawabnya dengan lirih. “Rumah yang abadi.” sambungnya.
“Maksudmu?” tanyaku memperjelas.
Aseel mengalihkan pandangannya padaku. Dan kali ini, untuk kesekian kalinya ia tersenyum, bagaikan bunga yang sedang mekar. Tiba-tiba timah panas dengan cepat menembus kepalanya. Cairan merah anyir tumpah begitu saja. Bunga yang sedang mekar itu tetap mekar, tapi tak merona lagi. Wajahnya yang lugu tiba-tiba pucat pasi seperti boneka yang patut dikasihani. Badannya tumbang ke pangkuanku. Jantungnya berhenti berdetak, nadinya berhenti berdenyut. Aku menggigit bibir, membendung tangis yang akan meluap. Tuhan, aku tak mampu melihat ini semua!
“Innalilahi wa inailaihi raji’un....” hanya itulah kalimat terakhir yang mampu kuucapkan sebelum semuanya menjadi gelap. Suram.
Aseel mungkin sudah tak ada lagi, tapi aku tahu satu hal: gadis kecil tak berdosa itu telah menemukan rumahnya, sebuah rumah yang abadi.
***
Rumah bukan hanya soal atap yang dapat meneduhkanmu dari butir-butir hujan. Bukan sekedar pondasi yang dapat menahan berat tubuhmu. Bukan juga dinding kokoh yang menghalau gemuruh angin. Bagi mereka, esensi rumah lebih daripada itu. Rumah adalah tanah dimana kau dilahirkan dan sejak saat itu kau berkewajiban untuk mempertahankannya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawamu.
(Dara Agusti Maulidya)
INFO:
Cerpen yang saya publikasikan di blog ini telah dibukukan bersama beberapa cerpen lainnya yang ditulis oleh Komunitas Nulis Bareng Peduli Bareng. Seluruh keuntungan penjualan akan digunakan untuk kegiatan sosial yang disalurkan melalui Indonesia Mengajar. Untuk pemesanan, dapat melalui Rumah 1000000 Cerita.
Read More..